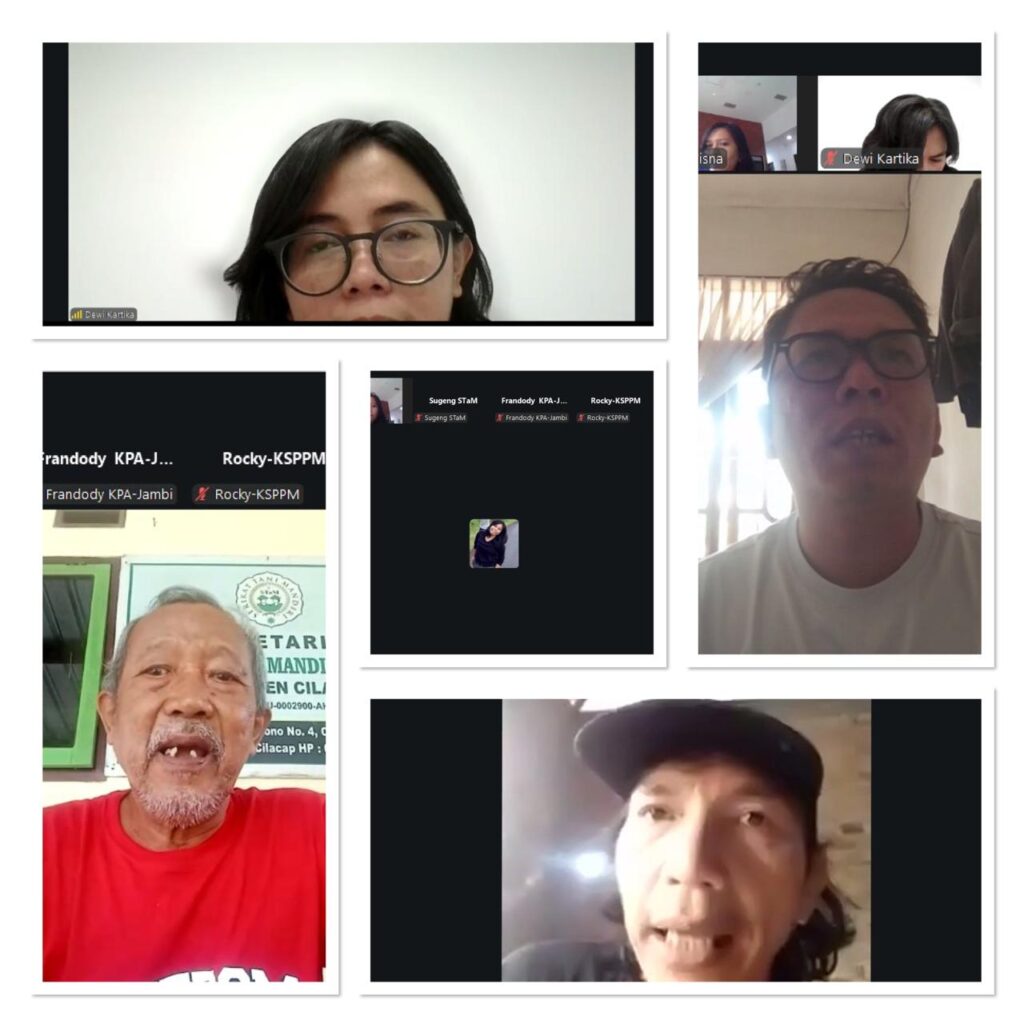Jakarta (parade.id)- Lebih dari sebulan sejak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria oleh DPR RI, tidak ada satu pun langkah konkret yang diambil untuk menyelesaikan konflik agraria struktural yang telah berlangsung puluhan tahun. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai Pansus yang dibentuk pada 2 Oktober 2025 itu hanya jadi pajangan politik tanpa gerak nyata.
“Sampai hari ini, pasca reses pada 3 November 2025—artinya DPR sudah bekerja lagi—kita masih belum melihat ada upaya-upaya percepatan bagaimana Pansus ini akan mulai bekerja,” tegas Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal KPA, dalam konferensi pers di Jakarta, Ahad (16/11).
Dewi menyebut Pansus yang beranggotakan 30 orang dari 8 fraksi itu belum memanggil kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penyelesaian konflik agraria yang kini semakin menumpuk dari Aceh hingga Papua.
“Jangan lagi pendekatannya case by case atau seperti pemadam kebakaran—baru turun kalau sudah ada korban, sudah ada demonstrasi besar-besaran, tapi akar masalah tidak pernah diselesaikan,” kritiknya.
Kriminalisasi Petani Terus Berlanjut
Sementara Pansus DPR tertidur, kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat justru semakin masif. Di Dairi, Sumatera Utara, puluhan masyarakat adat ditangkap karena mempertahankan kampungnya. Konflik dengan perusahaan Hutan Tanaman Industri Toba Pulp Lestari (TPL) di Tanah Batak juga tidak kunjung dituntaskan oleh pemerintahan Prabowo Subianto.
Rocky Pasaribu, Direktur Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Sumatera Utara, menyebut Sumut sebagai salah satu provinsi dengan konflik agraria terbanyak dalam dua tahun terakhir. “Belum selesai kasusnya Sorbatua, kemudian sudah muncul desa-desa yang lain yang mengalami kejadian yang serupa. Ini semua diakibatkan oleh konflik agraria yang dilakukan oleh perusahaan swasta, PTPN, dan kehutanan,” ungkapnya.
Bahkan masyarakat adat yang sudah mendapat Surat Keputusan (SK) pengakuan wilayah adat pun tetap tidak bisa berdaulat atas tanahnya. “Sampai hari ini beberapa komunitas masyarakat adat yang sudah mendapatkan SK belum bisa berdaulat untuk melakukan pengawasan dan pengaturan dalam wilayah adatnya, karena ternyata masih ada peraturan turunan seperti pengukuhan, penataan batas dan lain sebagainya,” kata Rocky.
Satgas PKH: Teror Baru di Kebun Rakyat
Di Provinsi Jambi, kehadiran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk melalui Perpres Nomor 05 Tahun 2025 justru menimbulkan teror baru bagi petani.
Frandody, Koordinator Wilayah KPA Jambi, mengungkapkan Satgas PKH memasang plang-plang di lahan garapan petani secara sepihak dan mengambang—tidak jelas di mana tepatnya batas kawasan hutan.
“Di Desa Lubuk Madrasah, plang dipasang di portal-portal perusahaan seluas 9.012 hektare. Ini bentuk teror bagi kaum tani, karena plang itu dipasang tidak tahu di mana tempatnya,” ujarnya.
Yang lebih ironis, perusahaan besar seperti Sinar Mas justru dibiarkan membuka Taman Nasional dengan pola kemitraan. “Yang semestinya ditertibkan adalah korporasi dan tuan-tuan tanah yang sebenarnya, tetapi ini sudah menyalahgunakan kewenangannya, akhirnya meluas ke kebun-kebun rakyat,” kritik Frandody.
Lebih parah lagi, penetapan kawasan hutan di Jambi pada 2021 ternyata cacat prosedur. “Berdasarkan Putusan MK dan UU Tahun 1949, ada tahapan: penunjukan, tata batas, pengukuran temu gelang, baru penetapan, baru pengukuhan. Tapi di Jambi 2021, penunjukan langsung ditetapkan. Ini sepihak,” tandas Frandody.
PTPN: Korporasi Negara Paling Kriminal
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) justru menjadi aktor utama konflik agraria. Rizky Anggriana Arimbi, Koordinator Wilayah KPA Sulawesi Selatan, menyebut PTPN sebagai “korporasi negara paling kriminal” yang telah melakukan kejahatan agraria secara kronis selama puluhan tahun.
“Hampir di seluruh Indonesia, PTPN berkonflik dengan masyarakat, dengan ribuan bahkan ratusan ribu keluarga petani. Sulsel tahun lalu merupakan provinsi yang letusan konflik agrariannya terbanyak di Indonesia,” papar Rizky.
Di sembilan kabupaten di Sulsel, hampir 100 ribu hektare tanah diklaim PTPN. Yang lebih mengejutkan, 60 persen HGU PTPN di beberapa kabupaten sudah habis—bahkan ada yang sudah berakhir 20 tahun lalu—tapi masih diklaim sebagai aset PTPN.
“Di Luwu Timur, petani transmigrasi dari Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang sudah memiliki sertifikat hak milik dikuasai oleh PTPN dalam 40 tahun terakhir yang tidak punya HGU, hanya izin lokasi,” ungkap Rizky.
Di Perkebunan Tebeng, Takalar, konflik PTPN meledak hampir setiap hari. “Dalam 1 bulan terakhir tidak kurang dari 20 petani dikriminalisasi. Terakhir ada 2 lagi yang langsung ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.
Setiap kali didesak untuk menyelesaikan konflik PTPN, jawaban pemerintah daerah, ATR/BPN, hingga kementerian selalu sama: “Ini sangat sulit karena berkaitan dengan aset BUMN. Harus ada pelepasan aktiva dari negara atau penghapusbukuan aset dari Kemenkeu. Kalau dilepaskan begitu saja, akan jadi temuan kehilangan aset dan pejabat bisa tersangkut indikasi korupsi.”
Cilacap: Warisan Kolonial yang Tak Kunjung Selesai
Di Jawa Tengah, konflik agraria masih mengacu pada Berita Acara Tata Batas (BATB) peninggalan penjajah tahun 1932 dan 1941. Sugeng Petrus, Ketua Serikat Tani Mandiri (STaM) Cilacap, mengungkapkan bahwa Gugus Tugas Reforma Agraria yang turun ke Cilacap pada 15 Mei 2023 justru lebih mengukuhkan klaim Perhutani dan perusahaan.
“Setelah diadakan verifikasi dan pengukuran ulang, mereka malah lebih mengukuhkan patok-patok yang telah dipasang perusahaan tahun 1972-1976, bukan mengacu BATB zaman penjajah. Tidak ada niatan menyelesaikan,” keluhnya.
Yang lebih menyakitkan, tanah-tanah produktif yang dirampas negara pasca peristiwa politik DI/TII tahun 50-an dan G30S/PKI kini diklaim sebagai kawasan hutan. “Dengan pergilas dan kasat mata, itu jelas-jelas dirampas oleh pemerintah,” ujar Sugeng.
Bahkan Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Menteri pernah menyaksikan panen raya di Desa Buluh Payung, Cilacap, pada 15 Februari 2023. “Beliau sempat menyampaikan, ‘Inilah yang harus diselesaikan, inilah yang patut dijadikan sumber pangan.’ Tapi nyatanya sampai sekarang, belum ada tanda-tanda untuk mengeksekusi,” tandas Sugeng.
Nasionalisasi Aset: Jalan Lambat yang Mengkhianati Rakyat
KPA juga mengkritik keras skema nasionalisasi aset yang kini sedang dipercepat pemerintah. Alih-alih mempercepat reforma agraria, pemerintah justru mengonsolidasikan tanah-tanah masyarakat menjadi Hak Pengelolaan (HPL) negara—baik melalui Bank Tanah, PTPN, maupun BUMN lainnya.
“Kementerian Agraria menawarkan solusi win-win berupa hak pakai di atas HPL BUMN. Ini menurunkan komitmen pemerintah. Padahal Perpres Nomor 62 Tahun 2023 sudah memandatkan redistribusi tanah dalam bentuk hak milik, bukan hak pakai,” tegas Dewi Kartika.
Dewi memperingatkan bahwa banyak tanah masyarakat, perkampungan, tanah pertanian produktif, bahkan wilayah adat, kini terancam dinasionalisasi menjadi HPL negara. “Ini bagian dari penyimpangan Hak Menguasai dari Negara. Konstitusi kita, Putusan MK, sudah menegaskan bahwa Hak Menguasai dari Negara bukan berarti negara memiliki tanah. Tidak boleh ada kewenangan yang sangat absolut, bahkan abuse of power dari negara,” jelasnya.
“Alih-alih mengidentifikasi tanah-tanah rakyat kemudian diregister, didaftarkan dalam sistem pertanahan, alih-alih menata ulang batas kawasan hutan dan wilayah adat, justru yang dipercepat adalah konsolidasi tanah oleh negara untuk menjadi aset negara. Ini salah kaprah,” kritik Dewi.
Ia menyebut ada “jalan cepat” untuk rakyat: keluarkan tanah-tanah perkampungan, tanah pertanian produktif, dan wilayah adat dari skema nasionalisasi aset, lalu langsung berikan hak milik kepada masyarakat. “Tapi yang ditempuh adalah jalan lambat: masuk dulu ke HPL negara, baru nanti—entah kapan—redistribusi. Ini semakin membuat jalan panjang masyarakat untuk mendapatkan keadilan agraria,” ujarnya.
865 Lokasi Prioritas Diabaikan
Pada Hari Tani Nasional 24 September 2025, KPA telah menyerahkan 865 lokasi prioritas reforma agraria seluas 1,76 juta hektare kepada pemerintah. Namun hingga kini tidak ada tindak lanjut konkret.
KPA juga mendesak Presiden Prabowo menertibkan dan mendistribusikan 7,35 juta hektare tanah terindikasi terlantar, 26,8 juta hektare tanah yang dimonopoli konglomerat, serta tanah-tanah masyarakat yang diklaim PTPN, Perhutani, dan klaim perhutanan negara pada 25 ribu desa.
“Dalam 1 tahun terakhir, dari sejak dilantik sampai memasuki awal tahun ke-2 pemerintahan Prabowo, kita masih belum melihat roadmap yang jelas bagaimana target reforma agraria ini hendak dijalankan,” keluh Dewi.
Pasca Hari Tani, KPA sudah bertemu dengan Menteri Kehutanan dan Menteri Agraria. “Kita masih melihat keinginan untuk mengulur-ulur, menunda-nunda, bahwa hak rakyat itu masih bisa lewat dialog-dialog biasa. Ini perlu penanganan extraordinary, karena konflik agraria ini bukan kasus biasa,” tegasnya.
Reforma Agraria Butuh Kepemimpinan Presiden
KPA mendesak Presiden Prabowo segera membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional (BPRAN) yang dipimpin langsung oleh Presiden. Menurut Dewi, kementerian dan lembaga yang ada—ATR/BPN, Kehutanan, BUMN, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian—justru menjadi sumber utama masalah agraria.
“Ada political will yang lemah, ada mindset yang terus dipelihara dan memilih zona aman, ada inkonsistensi kepada janji-janji reforma agraria. Ada paradoks kebijakan: janji reforma agraria berjalan, tapi di waktu bersamaan proyek-proyek pembangunan yang lapar tanah dan akan merampas tanah rakyat tetap terus bekerja,” paparnya.
Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, reforma agraria ditaruh di bawah Kemenko Ekonomi yang justru punya tujuan kontraproduktif dengan agenda reforma agraria. “Ada bias tujuan, ada bias kepentingan untuk orientasi ekonomi, bisnis, investasi. Yang terkalahkan adalah kepentingan keadilan sosial berbasis reforma agraria,” ungkap Dewi.
Kini di pemerintahan Prabowo, reforma agraria hendak digeser ke Kementerian Koordinator Infrastruktur. “Ini tidak akan menjawab masalah karena tetap tidak ada kewenangan dalam melakukan eksekusi untuk menuntaskan konflik agraria,” kritiknya.
Frandody dari Jambi menegaskan BPRAN harus dipimpin langsung Presiden karena akan melalui lintas sektoral—Kementerian Kehutanan, ATR/BPN, hingga BUMN. “Ini harus Presiden, karena tidak bisa seorang Menteri yang memimpinnya. Harus ada satu komando,” tegasnya.
Ribuan Tahun untuk Menuntaskan Konflik?
Dewi Kartika memperingatkan, jika konflik agraria terus diselesaikan case by case, akan butuh ribuan tahun untuk menuntaskan puluhan ribu kasus yang terus menumpuk.
“Rata-rata kasus konflik agraria hanya bisa selesai sudah 25 tahun, 30 tahun, baru ada penyelesaiannya. Kalau puluhan ribu kasus ini hanya diselesaikan case by case, bisa dibayangkan butuh ribuan tahun untuk menuntaskan semua konflik agraria yang semakin terakumulasi di wilayah Indonesia,” ujarnya.
KPA menuntut Pansus DPR segera bekerja sebagai balancing power untuk mengawasi kinerja Presiden dan kementerian terkait dalam pelaksanaan reforma agraria. “Sampai sekarang kami tidak melihat bagaimana proses Pansus itu bekerja untuk memanggil dan mempertanyakan progres kinerja pelaksanaan reforma agraria,” tandas Dewi.
Pertanyaannya kini: apakah Pansus DPR dan Presiden Prabowo akan serius menyelesaikan konflik agraria struktural yang telah memakan korban puluhan tahun, atau hanya akan jadi janji politik yang kembali mengkhianati petani dan masyarakat adat Indonesia?*